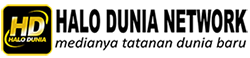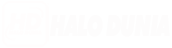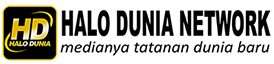Sekedar tulisan santai dan mungkin tidak berbobot, tapi lebih baik ditulis mungkin ada yang menganggap berbobot, selamat membaca
Jika dicermati, sepertinya ada tiga fase —entah adagium, jargon, atau paradigma— politik yang relatif dominan mewarnai (peradaban) perjalanan bangsa ini sejak proklamasi kemerdekaan dulu. Pertama, ialah adagium: “Politik sebagai panglima.” Tak bisa dielak, hal tersebut bahkan berlangsung hingga 2 (dua) orde yakni orde lama dan orde baru, dimana tertandai dengan adanya lembaga ekstra yudisial semacam Koopkamtib, “Petrus,” termasuk berlakunya UU Subversif dan lain-lain.

Tatkala orde baru runtuh, dan orde reformasi bergulir, tak pelak bahwa adagium (politik) pun berganti judul menjadi “hukum sebagai panglima” yang ditandai dengan lahirnya KPK beserta ornamen-ornamen pendukung semacam ICW serta menjamurnya LSM antikorupsi.
Agaknya, meski era reformasi masih berlangsung, akan tetapi terdapat “gaduh kecenderungan” di masyarakat bahwa adagium atau jargon tadi telah bergeser. Ya. Tidak lagi mengapresiasi hukum sebagai panglima, namun berubah menjadi “opini publik sebagai panglima.” Hiduplah pada zamannya. Itulah ungkapan bijak yang layak untuk memotret realitas perubahan jargon dimaksud.
Dan ini pula, fakta sosial politik di negeri kita yang tidak bisa disangkal siapapun. Artinya, dengan sekali klik atau enter contohnya, pendapat siapapun akan di-like dan/atau di-share kemana-mana oleh warga lain terutama publik di dunia maya bila ‘kicauan’-nya mengandung substansi aspirasi publik, baik yang pro maupun kontra.
Tak dapat dipungkiri pula, bahwa public trust dan/atau bahkan ketidakpercayaan publik terhadap individu, kelompok, golongan bahkan pemerintah justru bermula dari bagaimana “mereka” merespon opini publik. Jargon inilah yang kini beroperasional secara masiv di ruang-ruang sosial politik.