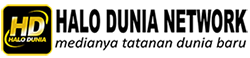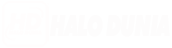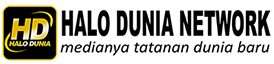Halodunia.net – Saat aku bangun jam lima pagi. Ternyata Dinda sudah tidak ada di rumah. Dinda pernah cerita kalau dia belakangan ini bekerja sebagai pemetik jagung. Perkebunan jagung memang menjadi salah satu sumber mata pencaharian warga kampung Mekar Sari.
Selesai salat subuh aku langsung mandi. Namun, sebelum beranjak ke kamar mandi, tak sengaja kulihat pintu kamar Mbok Ibah terbuka sedikit. Aku mendekati pintu itu untuk mencari tahu apakah Mbok Ibah sudah bangun atau belum.
“Mbok sudah bangun?” kudorong pintu kamar itu sedikit, lalu melongokkan kepala.
Mbok Ibah ternyata sudah bangun. Dia duduk di tepi tempat tidurnya sambil menunduk.
“Sudah, Nak,” jawabnya dengan suara yang serak kering.
“Oh ya sudah kalau begitu, Mbok. Saya mau mandi dulu ya,” kataku sambil tersenyum. Dia tidak menoleh kepadaku dan terus menunduk.
Aku pergi ke kamar mandi. Air di kampung ini sangat dingin. Mungkin karena lokasi kampung ini dekat dengan pegunungan. Saking dinginnya, tubuhku seketika menggigil. Saat sedang mandi, tiba-tiba ada seseorang memanggilku. Aku kenal itu suara Mbok Ibah.
“Nak ini handuknya,” kata Mbok Ibah dengan suaranya yang masih terdengar serak dan kering.
“Oh iya, Mbok. Wah jangan repot-repot. Aku udah bawa handuk kok, Mbok,” timpalku dari dalam kamar mandi.
Kudengar dia malah terkekeh lalu berkata, “Pakai handuk Mbok saja.”
Gayung yang kupegang seketika jatuh. Aku baru ingat kalau Mbok Ibah ini kan sudah tidak bisa berbicara. Aku seketika terdiam. Suaraku tercekat di tenggorokan. Suasana menjadi sangat mencekam. Di luar Mbok Ibah masih memanggilku sambil menawarkan handuk.
Baca Saja : Bioglass MCI Indonesia
“Ini pakai punya Mbok saja.”
Dari atas tembok kamar mandi, kulihat sebuah tangan yang menjulur panjang. Tangan itu menggenggam handuk warna biru. Jelas saja aku kaget hingga berteriak ketakutan sambil minta tolong. Aku jongkok sambil memeluk kaki. Aku tidak berani menatap ke atas.
Untungnya sesaat kemudian ada yang menggedor pintu kamar mandiku.
“Kenapa, Mbak?!” itu suara Dinda.
Segera kukenakan handuk lalu membuka pintu.
“Dinda, tadi Mbok kamu bisa ngomong terus tangannya panjang banget,” nada bicaraku terburu-buru.
“Masa sih, Mbak?” tanya Dinda sambil mengerutkan dahi.
“Iya, Dinda. Mbak takut banget,” aku memegang tangan Dinda.
“Mbok masih ada di kamar kok. Kalau nggak percaya coba cek aja,” Dinda mengajakku untuk melihat kamar Mbok Ibah.
“Takut, Din,” aku menggelengkan kepala.
“Ayo, Mbak…,” Dinda memaksa sambil menarik lenganku.
Pelan-pelan kudekati pintu kamarnya Mbok Ibah. Dinda mendorong pintu itu. Di dalam sana kulihat Mbok Ibah masih duduk di tepi tempat tidurnya. Dia menoleh ke arah kami lalu tersenyum sambil mengangguk ramah.
“Tuh kan… Mbok masih di kamarnya,” kata Dinda.
“Sumpah, Dinda. Mbak dengar jelas banget kalau Mbok kamu ngomong terus tangannya panjang banget.”
“Kayaknya Mbak masih ngelindur deh,” kata Dinda.
Aku menggelengkan kepala, “Ya sudah lupakan,” kataku. Aku rasa percuma bersikeras dengan orang yang tidak percaya padaku.
“Emang kamu habis dari mana?” tanyaku sambil menjauh dari kamar Mbok Ibah. Aku mengalihkan pembicaraan sambil menjauh dari kamar Mbok Ibah.
“Aku tadi di belakang rumah, Mbak. Habis bersih-bersih. Hari ini Mbak kerja ya?” tanya Dinda.
“Iya, Din. Mbak mau ganti pakaian dulu ya.”
“Mbak bidan kan? sebelum masuk ke kamar, Dinda malah bertanya lagi.
“Iya, Dinda.”
“Di kampung ini kalau ada yang melahirkan nggak suka pakai bidan Mbak.”
“Lho, kenapa? Masih pakai dukun ya?” aku mengerutkan dahi.
“Iya. Tapi di kampung ini bukan dukun namanya, tapi paraji.”
Aku mengangguk-angguk. Ini merupakan tantangan baru bagiku. Aku harus memberikan penyuluhan pada masyarakat agar mereka paham tentang keselamatan saat bersalin.
***
Pagi itu aku dijemput oleh Pak Sukra. Dia pegawai puskesmas. Pak Sukra pasti tahu dari warga kalau aku menyewa kamar di rumahnya Dinda.
Aku pun diantar ke puskesmas yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Dinda. Mungkin sekitar lima belas menit perjalanan. Jalan menuju puskesmas juga rusak parah. Aku dibonceng pakai motor bebeknya Pak Sukra.
“Kenapa jalanan di kampung ini rusak semua ya, Pak?”
“Ya beginilah, Mbak. Jarang ada pembangunan. Sekalinya dibangun aspalnya tipis banget. Ya palingan bertahan satu atau dua tahun udah rusak lagi.”
“Oh… begitu ya, Pak?”
“Iya, Mbak. Paling parah kalau musim hujan banyak orang yang jatuh dari motor karena jalannya licin, Mbak.”
Akhirnya kami tiba di puskesmas. Dilihat dari depan, puskesmas itu tampak seram, temboknya berlumut, catnya juga sudah pudar. Ada pohon beringin besar di depan gedung puskesmas itu.
“Kita sudah sampai, Mbak. Ini puskesmas Mekar Sari,” ucap Pak Sukra sambil tersenyum.
“Pak, itu di belakang puskesmas siapa?” tanyaku sambil menunjuk ke arah wanita yang berdiri di halaman belakang gedung.
Wanita itu menatap ke arah kami. Ia mengenakan daster dan tampak seperti sedang hamil tua. Dari tempatku berdiri saat ini, aku masih bisa melihat wujud wanita itu dengan jelas.
“Mana, Mbak?” Pak Sukra mencari sosok yang kutunjuk-tunjuk.
“Itu lho, Pak. Kayaknya dia lagi hamil tua,” aku masih melihat sosok itu.
Anehnya Pak Sukra tidak melihatnya. Padahal jelas-jelas wanita itu masih berdiri di halaman belakang puskesmas sambil menatap kami. Siapa wanita itu?
Baca Saja : MCI Indonesia Sabet Dua Kali Penghargaan MURI