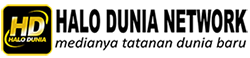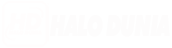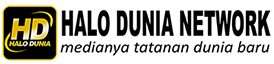Halodunia.net – Sebelum menceritakan pengalamanku ini, aku mau minta maaf kalau ada kesamaan tempat atau nama tokoh. Baiklah, sebenarnya aku tidak pandai bercerita. Tapi, aku rasa ini saat yang tepat untuk menceritakan ulang pengalamanku berdinas di sebuah puskesmas yang terletak di sebuah kampung terpencil.
Oh iya, perkenalkan dulu, aku Maya. Aku tuh seorang bidan. Setelah lulus kuliah, aku sempat kerja di klinik. Sebenarnya klinik itu milik kakak iparku. Kalau kalian pernah ke Balaraja, klinik tempatku bekerja tidak jauh dari pasar Balaraja. Selama dua tahun aku bekerja di sana.
Tahun 2016, pemerintah membuka lowongan CPNS. Aku iseng-iseng ikutan daftar. Sebenarnya aku hanya ingin tahu saja bagaimana tes CPNS itu dan tidak punya harapan tinggi bisa lolos tes. Tapi, Tuhan berkata lain. Alhamdulillah aku lolos CPNS, lalu ditugaskan ke kampung terpencil.
Nama kampungnya Mekar Sari. Di sana ada puskesmas yang kekurangan tenaga bidan. Oh iya, bukan kekurangan tapi tidak ada bidannya. Jadi bidan yang pernah tugas di sana minta dimutasi ke daerah lain. Dan… aku ditugaskan untuk mengisi kekosongan bidan di puskesmas itu.
Baca Saja: Bioglass Mci Kenali Dulu Produknya Dan Rasakan Manfaatnya
Aku tidak menyangka kalau kampung ini benar-benar terpencil. Mobil saja susah masuk karena jalannya rusak dan berlumpur kalau musim penghujan. Sesekali memang ada truk yang melintas. Tapi, para penumpang kerap terpaksa turun ramai-ramai mendorongnya karena ban terjebak di kubangan lumpur.
Aku sendiri naik ojek untuk sampai ke kampung Mekar Sari. Walau pada akhirnya tetap saja aku harus turun dari motor karena jalannya yang licin dan berbahaya. Dengan terpaksa aku menerobos kubangan lumpur. Sedangkan si bapak tukang ojek dengan susah payah mendorong motornya.
Saat itu aku sempat cemas karena sudah jam 5 sore. Tapi kami masih terjebak di jalan berlumpur ini.
“Ini masih jauh ya, Pak?” tanyaku sambil menyeimbangkan badan agar tidak tergelincir.
Tangan kananku menjinjing sepatu, sedangkan tas besarku diletakkan di depan jok motor.
“Udah dekat kok, Neng. Habis hutan pinus ini kita sampai di Mekar Sari,” jawabnya sambil menoleh ke arahku. Sejauh mata memandang, di sepanjang jalanan ini memang hutan pinus.
Sesampainya di kampung Mekar Sari, aku langsung mencari kos-kosan. Aku kesulitan mencari orang untuk bertanya. Kampung ini sepi sekali padahal masih sore. Untungnya aku bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk sendirian di depan rumahnya.
“Permisi, Bu, perkenalkan saya Maya. Saya bidan baru yang ditugaskan di kampung ini. Kalau mau sewa kosan di mana ya?” tanyaku.
“Oh, Mbak ini bidan baru,” dia menghampiriku sambil tersenyum ramah.
“Iya, Bu,” aku menyalaminya.
“Kenalkan, saya Minah. Kalau Mbak cari kosan di kampung ini ya nggak ada. Tapi Mbak bisa sewa kamar di rumah warga,” katanya.
“Nggak apa-apa saya sewa kamar aja. Kira-kira siapa ya yang berkenan kamarnya saya sewa?”
“Duh, kalau di rumah saya kamarnya terisi semua. Gimana kalau ke rumahnya Dinda? Bidan yang dulu juga tinggal di rumah Dinda,” katanya.
“Dinda?” tanyaku sambil mengerutkan dahi.
“Iya. Dia itu cuma tinggal berdua sama neneknya. Siapa tahu Dinda mau sewakan kamar di rumahnya buat Mbak Maya,” ujarnya.
“Boleh, Bu. Boleh minta tolong antar saya ke rumah Dinda kalau gitu.”
Dia pun mengantarku ke rumah Dinda. Aku tidak menyangka kalau Dinda ini ternyata masih muda. Umurnya baru 19 tahun. Dia anak yatim piatu dan sudah putus sekolah. Selama bertahun-tahun Dinda mengurus neneknya yang sudah sangat renta.
Rumah Dinda cukup besar. Katanya rumah itu peninggalan orang tuanya. Ada empat kamar dan hanya dua yang diisi. Aku menyewa kamar bekas bidan yang pernah bertugas di kampung ini.
“Itu nenekku. Namanya Mbok Ibah. Dia udah nggak bisa ngomong,” Dinda membuka kamar neneknya. Dia memperkenalkan neneknya padaku.
Kulihat wanita tua itu sedang duduk di tepi tempat tidurnya. Seluruh rambutnya putih semua. Dia mengenakan kain batik yang warnanya sudah pudar dan baju kebaya usang. Perlahan wanita itu mendongak ke arahku dan dia tersenyum.
“Mbok, saya Maya yang mau sewa kamar di rumah ini,” sapaku dari pintu kamar.
Tentu saja dia tidak bisa menjawab. Tapi aku yakin dia juga menyapaku dalam hatinya.
Dinda menutup kembali pintu kamar neneknya. Engsel pintu itu mungkin sudah berkarat sehingga menimbulkan bunyi yang cukup nyaring saat ditutup.
Dinda lalu membawaku ke kamar yang mau aku sewa. Walau temboknya usang dan retak, tapi kamar itu tampak bersih. Ada ranjang besi jadul dan kasur kapuk di sana. Ada juga lemari pakaian yang dilengkapi dengan cermin besar.
“Ini kamarnya, Mbak. Semoga betah tinggal di sini,” ucap Dinda. Dari tadi aku tidak melihatnya tersenyum sedikit pun. Mungkin Dinda orang yang pendiam.
“Iya, Dinda. Terima kasih banyak udah mau terima aku di rumah kamu. Oh iya, aku punya sesuatu buat kamu,” segera kubuka tas besar yang kubawa.
“Ini buat kamu. Kamu suka cokelat, kan?” tanyaku.
Dia mengangguk lalu mengambil cokelat itu.”Terima kasih Mbak,” katanya. “Kalau ada apa-apa jangan sungkan panggil saya aja ya, Mbak,” tambah Dinda.
“Iya, Dinda,” timpalku.
Malam itu selesai mandi aku langsung tidur karena sangat lelah. Pintu kamar kukunci rapat, lampunya kumatikan. Hari yang sangat melelahkan. Aku harus istirahat karena besok sudah mulai bertugas di puskesmas.